BENGKULU, Caribengkulu.com– Di jantung Kota Bengkulu, tepatnya di Jalan Letjen Soeprapto, berdiri sebuah bangunan yang lebih dari sekadar rumah ibadah; ia adalah sebuah artefak sejarah yang hidup, sebuah monumen yang menjadi saksi bisu persilangan antara spiritualitas Islam, dinamika sosio-ekonomi, dan gelora nasionalisme. Masjid Jamik Bengkulu, yang juga dikenal luas dengan julukan 'Masjid Bung Karno', memegang posisi unik dalam lanskap kultural Indonesia. Bangunan ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan bagi masyarakat, tetapi juga diakui secara resmi oleh negara sebagai peninggalan bersejarah yang tak ternilai, berstatus Cagar Budaya Nasional yang dilindungi oleh kekuatan hukum. Ia adalah ruang komunal yang dinamis, menjadi pusat kegiatan spiritual, sosial, hingga destinasi wisata religi yang ramai dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai penjuru. Status ganda ini menempatkan Masjid Jamik Bengkulu dalam sebuah dialog konstan antara pelestarian masa lalu dan pemenuhan kebutuhan masa kini.

Berita ini bertujuan untuk mengupas secara tuntas dan mendalam perjalanan transformatif Masjid Jamik Bengkulu. Analisis akan dimulai dari cikal bakalnya sebagai sebuah surau sederhana yang didirikan di tengah geliat komunitas perantau, bertransformasi menjadi sebuah mahakarya arsitektur di tangan Ir. Soekarno yang sarat dengan filosofi kebangsaan dan perlawanan budaya, hingga menelaah bagaimana warisan monumental ini berdialog dengan tantangan zaman modern. Melalui penelusuran yang komprehensif, berita ini akan membedah bagaimana setiap lapis sejarah, setiap detail arsitektur, dan setiap fungsi sosial dari masjid ini saling berkelindan, menjadikannya salah satu ikon paling penting di Bumi Rafflesia.
Cikal Bakal dan Era Awal: Dari Surau Lamo ke Pusat Komunitas
Sejarah panjang Masjid Jamik Bengkulu berakar dari sebuah bangunan sederhana yang jauh dari kemegahan arsitektural yang dimilikinya saat ini. Cikal bakalnya adalah manifestasi dari kebutuhan spiritual sebuah komunitas yang sedang tumbuh dan berjuang membangun eksistensinya di tanah rantau.
Pada mulanya, tempat ibadah ini dikenal dengan nama "Surau Lamo". Sesuai dengan namanya, bangunan ini pada awalnya sangat bersahaja, terbuat sepenuhnya dari material lokal yang sederhana, seperti dinding dan tiang dari kayu, serta atap yang terbuat dari anyaman daun rumbia. Lantainya pun belum menggunakan tegel atau semen, melainkan masih berupa lantai sederhana yang kerap menjadi becek dan kotor saat musim hujan tiba.
Lokasi awal Surau Lamo ini berada di sebuah area yang kini dikenal sebagai Kelurahan Bajak, Kecamatan Teluk Segara, tidak jauh dari kompleks pemakaman pahlawan nasional Sentot Alibasyah Prawiradirja. Namun, lokasi ini memiliki kelemahan signifikan: sering tergenang air dan rawan banjir. Kondisi geografis yang kurang menguntungkan ini mendorong komunitas pada awal abad ke-18 untuk memindahkan surau tersebut ke lokasi yang lebih baik. Lokasi baru yang dipilih adalah tempat masjid berdiri hingga hari ini, yakni di Jalan Soeprapto, sebuah area yang pada masa itu berkembang menjadi kawasan yang lebih strategis karena kedekatannya dengan pusat-pusat perdagangan dan aktivitas masyarakat. Pemindahan ini menandai babak baru bagi Surau Lamo, yang secara bertahap mulai berkembang menjadi titik sentral kehidupan sosial dan keagamaan.
Berbagai catatan sejarah secara konsisten menyebutkan bahwa pendiri Surau Lamo adalah seorang tokoh bernama Daeng Makulle, yang digambarkan sebagai seorang "Datuk Dagang dari Tengah Padang". Namun, penelusuran yang lebih mendalam mengungkap identitas dan peran Daeng Makulle yang jauh lebih kompleks dan signifikan. Daeng Makulle bukanlah penduduk asli Bengkulu. Ia adalah seorang keturunan bangsawan Bugis, putra dari Daing Mabela, seorang perantau dari Wajo, Sulawesi Selatan. Kedatangannya ke Bengkulu merupakan bagian dari gelombang migrasi orang Bugis yang mencari peluang ekonomi dan pengaruh politik. Kunci dari keberhasilannya dalam membangun pengaruh di Bengkulu adalah melalui aliansi strategis: Daeng Makulle menikah dengan Datuk Nyai, putri dari Pangeran Mangku Raja, seorang penguasa lokal yang mengendalikan wilayah Sungai Lemau.
Pernikahan ini menjadi titik balik yang memberinya legitimasi politik dan akses terhadap sumber daya. Ia kemudian diangkat menjadi "Datuk Dagang," sebuah posisi terhormat yang memberinya wewenang dalam urusan perdagangan di wilayah tersebut. Lebih dari itu, sebagai bagian dari hubungan kekerabatan tersebut, Pangeran Mangku Raja menganugerahinya sebidang tanah luas yang masih berupa belukar. Daeng Makulle kemudian membuka lahan tersebut dan mendirikan sebuah perkampungan baru untuk keluarga dan komunitasnya, yang ia namai "Kampung Tengah Padang". Diperkirakan, di pusat pemukiman baru inilah Surau Lamo ia dirikan.
Dengan demikian, pendirian Surau Lamo tidak dapat dipandang sebagai peristiwa yang terisolasi. Ia secara intrinsik terkait erat dengan proses yang lebih besar, yaitu migrasi komunitas Bugis, pembentukan aliansi politik melalui pernikahan antara pendatang dan elite lokal, serta pendirian sebuah pusat ekonomi baru. Surau tersebut tidak hanya dibangun sebagai fasilitas ibadah, tetapi "ditanam" sebagai jangkar spiritual dan sosial bagi sebuah komunitas perantau yang sedang membangun identitas dan mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi-politiknya. Pemilihan lokasi di Kampung Tengah Padang adalah sebuah langkah strategis untuk melayani dan melegitimasi pusat komunitas yang baru ia bangun. Sejarah awal masjid ini, oleh karena itu, adalah cerminan dari proses akulturasi, konsolidasi kekuasaan, dan pembangunan komunitas yang dinamis di Bengkulu pada abad ke-18 dan ke-19.
Titik Balik Sejarah: Sentuhan Arsitektural Soekarno di Masa Pengasingan (1938-1942)
Memasuki abad ke-20, kondisi Masjid Jamik yang telah menggantikan Surau Lamo mulai memprihatinkan. Bangunan yang sederhana itu tidak lagi mampu menampung jemaah yang semakin banyak dan kondisinya pun dianggap tidak layak. Titik balik dalam sejarah masjid ini terjadi dengan kedatangan seorang tokoh yang akan mengubah wajah dan takdirnya untuk selamanya: Ir. Soekarno.
Pada awal dekade 1930-an, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, de Jonge, mengeluarkan kebijakan represif untuk mempersempit ruang gerak kaum pergerakan nasional. Salah satu kebijakan utamanya adalah larangan berkumpul dan mengadakan rapat, dengan ancaman hukuman buang (pengasingan) bagi para pelanggarnya. Soekarno, sebagai salah satu motor utama pergerakan, menjadi target kebijakan ini. Akibat aktivitas politiknya, ia ditangkap dan menjalani hukuman pengasingan, pertama ke Flores pada tahun 1930, dan kemudian dipindahkan ke Bengkulu pada tahun 1938.
Di Bengkulu, Soekarno dan keluarganya tinggal di sebuah rumah yang lokasinya tidak terlalu jauh dari Masjid Jamik, hanya sekitar satu setengah kilometer. Pada saat yang bersamaan, di kalangan masyarakat dan para pemuka agama setempat—yang dikenal sebagai "Kaum Tuo"—telah berkembang keinginan kuat untuk merenovasi Masjid Jamik yang kondisinya sudah usang. Pertemuan antara kebutuhan masyarakat dan kehadiran seorang tokoh pergerakan yang juga seorang insinyur arsitektur inilah yang membuka jalan bagi salah satu warisan paling ikonik Bung Karno di Bumi Rafflesia.
Melihat keahlian yang dimiliki Soekarno, masyarakat dan para Kaum Tuo mencapai mufakat untuk memintanya membantu merancang ulang masjid mereka. Namun, proses ini sama sekali tidak berjalan mulus. Sebagai seorang tahanan politik yang diawasi ketat oleh pemerintah kolonial, gagasan-gagasan pembaruan yang dibawa Soekarno pada awalnya kurang diterima, bahkan ditolak oleh sebagian kalangan. Catatan sejarah menyebutkan bahwa Soekarno harus menghadapi "perlawanan" dan terlibat dalam "perdebatan yang alot" dengan kaum-kaum berpengaruh dan para tetua adat saat itu.
Keterlibatan Soekarno dalam proyek Masjid Jamik, dengan demikian, melampaui sekadar kontribusi teknis; ia menjadi sebuah manuver politik dan budaya yang sangat cerdas. Menyadari posisinya sebagai orang luar yang perlu membangun kepercayaan, Soekarno tidak memaksakan gagasannya secara frontal. Sebaliknya, ia menggunakan pendekatan budaya yang lebih halus untuk mendekati masyarakat. Salah satu strateginya yang tercatat adalah dengan membentuk sebuah sanggar kesenian bernama "Monte Carlo". Awalnya merupakan sebuah klub musik lokal, sanggar ini dikelola oleh Soekarno menjadi kelompok sandiwara musik yang berhasil menarik simpati dan membangun jembatan komunikasi dengan warga setempat.
Melalui pendekatan kultural inilah Soekarno secara bertahap berhasil mengubah persepsi publik terhadapnya. Permintaan untuk merenovasi masjid kemudian menjadi panggung utama baginya untuk menunjukkan niat baik, keahlian, dan visinya. Dengan mengatasi perlawanan melalui dialog yang persuasif, ia akhirnya berhasil meyakinkan semua pihak dan mendapatkan kepercayaan penuh untuk memimpin proyek desain tersebut. Proses ini menjadi sebuah prototipe awal dari gaya kepemimpinan Soekarno yang kelak akan sering ia gunakan: memanfaatkan simbol-simbol budaya dan proyek-proyek monumental untuk menyatukan masyarakat, membangun identitas, dan menggalang dukungan. Masjid Jamik menjadi salah satu kanvas pertamanya untuk melukiskan visi besar tentang Indonesia.
Setelah rancangan arsitekturnya disetujui, proyek renovasi pun dimulai. Semangat kolaborasi menjadi napas dari pembangunan ini. Pendanaan utama proyek tidak berasal dari pemerintah kolonial, melainkan murni dari swadaya dan gotong royong masyarakat Bengkulu. Hal ini menunjukkan betapa besar keinginan dan dukungan komunitas terhadap perwujudan masjid baru yang lebih representatif. Untuk material bangunan, sumber daya didatangkan dari berbagai penjuru wilayah Bengkulu. Catatan sejarah menyebutkan bahwa material-material penting, kemungkinan besar kayu berkualitas, didatangkan dari Desa Air Dingin di Kabupaten Rejang Lebong serta dari wilayah Ketahun di Kabupaten Bengkulu Utara. Kolaborasi dalam pengadaan sumber daya ini semakin memperkuat ikatan kepemilikan masyarakat terhadap masjid tersebut, menjadikannya sebuah karya bersama yang lahir dari keringat dan harapan kolektif.
Analisis Arsitektur: Filosofi Anti-Kolonial dan Akulturasi Budaya Nusantara dalam Karya Soekarno
Desain Masjid Jamik Bengkulu karya Soekarno bukanlah sekadar sebuah rancang bangun, melainkan sebuah manifesto. Di dalamnya terkandung gagasan-gagasan mendalam tentang identitas, perlawanan budaya, dan visi kebangsaan. Soekarno menggunakan arsitektur sebagai medium untuk "menulis" pemikirannya dalam bentuk beton, kayu, dan ruang.
Salah satu keputusan paling fundamental yang diambil Soekarno adalah penolakannya yang tegas terhadap gaya arsitektur asing yang dominan pada masa itu. Ia secara eksplisit tidak ingin menerapkan desain bergaya Eropa yang identik dengan kolonialisme, maupun gaya Timur Tengah yang sering dianggap sebagai standar arsitektur Islam. Soekarno memiliki gayanya sendiri, sebuah pendekatan yang oleh sejarawan arsitektur Yuke Ardhiati disebut sebagai "gaya antikolonial".
Gaya ini merupakan ciri khas karya-karya arsitektur Soekarno pada periode 1926-1945, yang secara konsisten mengedepankan padu padan antara elemen-elemen arsitektur vernakular Nusantara dengan konsep ke-Indonesiaan yang modern. Dalam konteks Masjid Jamik, ini adalah sebuah pernyataan politik yang kuat. Dengan menolak gaya kolonial dan gaya yang dianggap "asing" lainnya, Soekarno secara arsitektural mendeklarasikan kemerdekaan budaya. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu menjadi peniru Barat maupun Timur; bangsa ini memiliki kekayaan intelektual dan estetika untuk menciptakan identitasnya sendiri. Masjid Jamik, dengan demikian, menjadi sebuah prototipe arsitektur untuk sebuah bangsa yang berdaulat dan berdikari.
Soekarno tidak merombak total struktur lama Surau Lamo, melainkan melakukan modifikasi dan penambahan yang transformatif sambil tetap mempertahankan beberapa elemen dasar seperti denah yang simetris. Setiap elemen yang ia rancang memiliki makna dan filosofi yang mendalam.
Ciri yang paling menonjol dan ikonik dari masjid ini adalah atapnya yang berbentuk limasan bertingkat tiga, atau dikenal sebagai atap tumpang. Bentuk atap ini merupakan sebuah sintesis brilian dari corak arsitektur tradisional Jawa dan Sumatra. Secara filosofis, tiga tingkatan atap ini melambangkan tiga pilar fundamental dalam ajaran Islam, yaitu Iman, Islam, dan Ihsan. Namun, di balik makna eksplisit ini, terdapat sebuah pernyataan budaya yang lebih dalam. Penggunaan atap tumpang adalah sebuah apropriasi bentuk atap pra-Islam yang lazim ditemukan pada bangunan suci Nusantara (seperti pendopo, pura, atau balai adat) ke dalam konteks masjid. Ini adalah penegasan visual bahwa ke-Indonesiaan dan ke-Islaman dapat bersinergi secara harmonis, sebuah gagasan sentral dalam pemikiran Soekarno tentang negara-bangsa. Selain itu, atap yang menjulang tinggi hingga sekitar 7 meter juga memiliki fungsi praktis yang sangat sesuai dengan iklim tropis Bengkulu, yaitu menciptakan sirkulasi udara alami yang baik sehingga ruang interior masjid terasa sejuk dan nyaman.
Di puncak tertinggi atap, terdapat sebuah ornamen hiasan yang disebut kemuncak atau mustaka. Konon, bentuk kemuncak ini terinspirasi dari Gada Rujakpolo, senjata milik Bima, salah satu tokoh Pandawa dalam epos Mahabharata yang menjadi favorit Soekarno. Pilihan simbol ini adalah sebuah contoh sinkretisme budaya yang sangat disengaja. Soekarno dengan berani menyandingkan simbolisme dari epos Hindu-Jawa dengan sebuah bangunan suci Islam. Ini adalah penegasan identitas budaya Indonesia yang plural dan berlapis, sebuah penolakan terhadap puritanisme dan perayaan atas kekayaan warisan Nusantara sebagai fondasi bangsa. Kemuncak ini melambangkan kekuatan, keteguhan, dan keperkasaan.
Ruang utama dan serambi masjid ditopang oleh total 19 buah pilar. Pilar-pilar utama di serambi memiliki bentuk segi delapan yang khas. Bagian atas pilar-pilar dihiasi dengan ukiran kayu bermotif sulur-suluran yang dicat kuning gading, serta beberapa di antaranya memiliki ukiran kaligrafi ayat-ayat Al-Quran. Desain pilar dengan ukiran detail ini disebut-sebut memiliki kemiripan dengan karya-karya Soekarno lainnya saat ia bekerja bersama mentornya, Prof. Charles Prosper Wolff Schoemaker, yang menunjukkan adanya kesinambungan dalam gaya arsitekturalnya. Pengulangan pilar-pilar ini secara teratur (ritme) menciptakan sebuah harmoni visual yang menenangkan dan agung di dalam ruang masjid.
Soekarno melakukan dua perubahan struktural yang esensial. Pertama, ia menaikkan lantai masjid hingga 30 cm dari permukaan tanah. Kedua, ia meninggikan dinding bangunan hingga 2 meter lebih tinggi dari sebelumnya. Kedua intervensi ini, meskipun terlihat sederhana, memberikan dampak psikologis yang signifikan. Ruangan menjadi terasa jauh lebih lapang, megah, dan agung, sehingga meningkatkan martabat bangunan sebagai pusat ibadah komunal.
Secara teknis, bangunan hasil rancangan Soekarno terdiri dari tiga bagian utama yang saling menyatu: bangunan inti (ruang shalat utama) berdenah bujur sangkar dengan ukuran presisi 14,65 x 14,65 meter; serambi (teras depan) berbentuk persegi panjang dengan ukuran 11,46 x 7,58 meter, berfungsi sebagai ruang transisi; dan tempat wudhu. Soekarno memadukan material modern dan tradisional. Dinding menggunakan bata yang kokoh, sementara pilar-pilar utama dan plafon menggunakan kayu jati berkualitas tinggi yang memberikan kesan hangat dan alami. Untuk fondasi tempat wudhu, digunakan pasangan batu karang yang kuat. Salah satu detail unik adalah desain mimbar khutbah. Alih-alih menggunakan mimbar kayu portabel, Soekarno merancang mimbar permanen yang terbuat dari pasangan bata dengan gaya yang terinspirasi dari arsitektur Istanbul, dilengkapi dengan atap berupa dua kubah kecil dari bahan aluminium, menunjukkan keterbukaan Soekarno dalam mengadopsi pengaruh global yang kemudian diadaptasi secara kreatif ke dalam konteks lokal.
Status, Peran, dan Signifikansi Kontemporer: Jantung Spiritual dan Magnet Wisata
Setelah melewati berbagai fase sejarah, Masjid Jamik Bengkulu kini menempati posisi yang mapan dan multifungsi dalam kehidupan masyarakat Bengkulu. Signifikansinya tidak hanya terletak pada masa lalunya yang gemilang, tetapi juga pada perannya yang hidup dan relevan di masa sekarang.
Pengakuan tertinggi atas nilai sejarah dan arsitektur masjid datang pada tahun 2004, ketika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia secara resmi menetapkannya sebagai Benda Cagar Budaya. Status hukum ini kemudian diperkuat dan dilindungi lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Penetapan ini memiliki implikasi hukum yang sangat penting. Sebagai cagar budaya, keaslian bangunan masjid harus dipertahankan. Setiap upaya renovasi, restorasi, atau pemugaran tidak boleh dilakukan secara sembarangan dan dilarang mengubah bentuk asli yang dirancang oleh Soekarno. Semua tindakan perbaikan harus mengikuti kaidah-kaidah pelestarian cagar budaya yang ketat. Status ini, di satu sisi, menjadi benteng pelindung yang menjaga warisan Soekarno dari perubahan yang tidak semestinya. Namun, di sisi lain, ia menciptakan sebuah tantangan yang kompleks dalam menyeimbangkan kebutuhan konservasi dengan fungsionalitas bangunan sebagai pusat kegiatan komunitas yang terus berkembang.
Jauh dari sekadar menjadi monumen beku, Masjid Jamik adalah jantung spiritualitas yang berdenyut kencang bagi masyarakat Kota Bengkulu. Fungsi utamanya sebagai tempat penyelenggaraan ibadah shalat fardhu lima waktu dan shalat Jumat berjalan secara rutin dan selalu ramai oleh jemaah. Lebih dari itu, masjid ini menjadi pusat bagi berbagai kegiatan keagamaan dan sosial. Berbagai acara untuk memperingati hari-hari besar Islam, sesi dakwah dan tabligh akbar, serta pengajian rutin untuk berbagai kalangan diselenggarakan secara berkala. Masjid ini juga mengambil peran penting dalam pendidikan Islam non-formal melalui penyelenggaraan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) bagi anak-anak. Secara sosial, perannya meluas hingga menjadi wadah pemersatu. Beberapa sumber menyebutkan bahwa masjid ini kerap menjadi lokasi untuk kegiatan lintas agama, seperti dialog antar-iman dan kegiatan sosial bersama yang ditujukan untuk masyarakat luas tanpa memandang latar belakang. Ini membuktikan bahwa Masjid Jamik berhasil mewujudkan fungsinya tidak hanya sebagai tempat ibadah vertikal kepada Tuhan, tetapi juga sebagai pusat kegiatan horizontal yang memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat.
Kombinasi antara keunikan arsitektur, nilai filosofis yang mendalam, dan keterikatan sejarahnya yang tak terpisahkan dengan proklamator kemerdekaan Indonesia, Bung Karno, menjadikan Masjid Jamik sebagai magnet bagi para wisatawan. Ia telah menjadi salah satu destinasi wisata religi dan sejarah utama di Provinsi Bengkulu. Pengunjung yang datang tidak hanya berasal dari masyarakat lokal, tetapi juga dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan mancanegara. Mereka datang untuk shalat, mengagumi keindahan arsitekturnya, dan meresapi jejak sejarah perjuangan bangsa yang melekat pada dinding-dindingnya. Julukan populer 'Masjid Bung Karno' yang melekat erat menjadi bukti betapa kuatnya citra masjid ini dalam ingatan kolektif sebagai salah satu karya monumental sang Bapak Bangsa.
Status ganda masjid sebagai cagar budaya yang harus dijaga keasliannya (statis) dan sebagai pusat komunitas yang hidup (dinamis) menciptakan sebuah tensi yang menarik, sebuah "paradoks pelestarian". Di satu sisi, ada mandat hukum untuk membekukan bangunan dalam kondisi historisnya yang otentik, seperti yang diamanatkan oleh UU Cagar Budaya. Di sisi lain, sebagai pusat kegiatan yang aktif, masjid dihadapkan pada kebutuhan nyata dari jemaah yang terus bertambah, yang memerlukan fasilitas modern, ruang yang lebih luas, dan kenyamanan yang sesuai dengan standar masa kini. Konflik potensial pun muncul; misalnya, kebutuhan untuk memperluas atau memodernisasi tempat wudhu dapat berbenturan dengan keharusan untuk mempertahankan struktur asli yang dirancang Soekarno. Oleh karena itu, pengurus masjid dan pemerintah daerah terus-menerus dihadapkan pada sebuah dilema: bagaimana cara melayani kebutuhan jemaah masa kini secara optimal tanpa merusak atau mengurangi otentisitas warisan sejarah yang tak ternilai untuk generasi mendatang? Setiap keputusan terkait pemeliharaan atau renovasi menjadi sebuah negosiasi yang rumit antara tuntutan masa lalu, masa kini, dan visi untuk masa depan.
Kondisi Terkini, Pemeliharaan, dan Wacana Publik: Tantangan di Balik Kemegahan
Memasuki dekade ketiga abad ke-21, Masjid Jamik Bengkulu menghadapi realitas pemeliharaan bangunan bersejarah yang kompleks. Di balik kemegahan nama besar dan statusnya sebagai cagar budaya, terdapat tantangan-tantangan praktis yang menjadi wacana publik dan memerlukan perhatian serius.
Secara umum, masjid ini menyediakan fasilitas yang sangat lengkap untuk melayani kebutuhan jemaah. Tersedia tempat wudhu yang memadai dan terpisah untuk pria dan wanita, kamar mandi/WC, area parkir yang cukup luas, serta perlengkapan ibadah seperti mukena, sarung, dan Al-Qur'an yang dapat digunakan oleh umum. Fasilitas penunjang seperti sound system, genset, hingga perlengkapan untuk pengurusan jenazah juga tersedia, menunjukkan manajemen yang berupaya melayani komunitas secara komprehensif.
Namun, dari segi kondisi fisik bangunan, beberapa laporan dari beberapa tahun terakhir menyoroti adanya sejumlah masalah. Sebuah tinjauan lapangan yang didokumentasikan pada tahun 2019 mengungkap beberapa titik kerusakan. Atap seng dilaporkan mengalami kebocoran di beberapa bagian, yang indikasinya terlihat dari adanya bercak-bercak air pada plafon kayu di ruang utama. Pengecatan ulang atap yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya dengan cara memasang pijakan papan yang dipakukan langsung ke seng telah meninggalkan lubang-lubang kecil yang justru berpotensi menjadi sumber kebocoran baru. Selain itu, cat pada dinding dan atap juga tampak mulai memudar, dan penataan halaman di beberapa sisi dinilai kurang terawat.
Hingga saat ini, masjid tercatat telah mengalami setidaknya tiga kali renovasi besar. Salah satu renovasi penting pasca-penetapan sebagai cagar budaya adalah pembangunan tempat wudhu baru di sisi selatan halaman pada tahun 2013. Untuk menjaga agar bangunan baru tidak menutupi fasad utama masjid yang bersejarah, tempat wudhu ini dibangun di bawah tanah (sublevel), sebuah solusi desain yang cerdas untuk mengakomodasi peningkatan jumlah jemaah, terutama saat shalat Jumat dan hari raya, tanpa mengganggu visual bangunan utama.
Meskipun demikian, pemeliharaan rutin tetap menjadi sebuah tantangan. Sebuah laporan berita dari Radio Republik Indonesia (RRI) pada Agustus 2023 melukiskan gambaran yang lebih gamblang. Laporan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa Masjid Jamik "memerlukan perhatian Pemda" dan seolah "tengah meratap dalam keheningan". Hal ini mengindikasikan bahwa dana operasional dan pemeliharaan sehari-hari sangat bergantung pada infak dan sedekah dari jemaah, yang jumlahnya mungkin tidak selalu cukup untuk menutupi biaya perawatan sebuah bangunan cagar budaya yang besar dan tua.
Menjawab kekhawatiran publik dan kondisi fisik bangunan, pada Maret 2024, muncul berita bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu telah merencanakan proyek pemugaran dan penataan komprehensif untuk Masjid Jamik Bengkulu. Proyek ini, yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2025, juga mencakup penataan ikon sejarah lainnya, yaitu Benteng Marlborough. Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Drs. Khairil Anwar, M.Si, menyatakan bahwa tujuan dari rencana ini adalah untuk membuat masjid menjadi "lebih representatif". Pernyataan ini menarik karena ia juga secara eksplisit menambahkan bahwa penataan tersebut akan dilakukan dengan "tetap memperhatikan nilai sejarahnya yang tinggi". Pernyataan ini secara langsung mengakui adanya tensi antara modernisasi ("representatif") dan preservasi ("nilai sejarah"), yang menjadi inti dari tantangan pengelolaan masjid.
Terdapat sebuah pergeseran narasi yang menarik untuk dicermati. Secara historis dan dalam skala nasional, Masjid Jamik adalah monumen agung, mahakarya Bung Karno, dan simbol kebanggaan bangsa. Namun, dalam diskursus lokal dan kontemporer, ia juga menjadi subjek dari keluhan-keluhan yang sangat praktis dan membumi: atap yang bocor, cat yang pudar, dan ketergantungan pada birokrasi pemerintah untuk pemeliharaan. Ini menyoroti adanya kesenjangan antara status simbolis sebuah monumen dan realitas pragmatis pemeliharaannya sehari-hari. Keberlangsungan warisan arsitektur Soekarno ini kini tidak hanya bergantung pada ingatan kolektif dan kebanggaan nasional, tetapi juga sangat ditentukan oleh faktor-faktor konkret seperti alokasi anggaran dalam APBD, prioritas politik pemerintah daerah, dan kompetensi teknis dari tim pemugaran yang akan ditunjuk. Masa depan fisik masjid akan sangat bergantung pada seberapa baik pemerintah daerah mampu menerjemahkan nilai sejarah yang tak ternilai menjadi tindakan konservasi yang efektif dan berkelanjutan.
Kesimpulan: Warisan Abadi dan Tantangan Masa Depan Masjid Jamik Bengkulu
Perjalanan Masjid Jamik Bengkulu adalah sebuah epik yang merentang selama tiga abad, bertransformasi dari sebuah surau kayu sederhana menjadi sebuah monumen arsitektur nasional yang sarat makna. Berita ini telah mengupas secara mendalam evolusinya, dimulai dari pendiriannya sebagai Surau Lamo yang menjadi pilar sosio-ekonomi bagi komunitas perantau Bugis di bawah kepemimpinan Daeng Makulle, hingga mencapai puncaknya sebagai kanvas ideologis bagi Ir. Soekarno. Di tangan Soekarno, masjid ini tidak hanya direnovasi secara fisik, tetapi juga diresapi dengan jiwa kebangsaan, menjadi sebuah manifesto anti-kolonial yang tertuang dalam bahasa arsitektur.
Warisan Masjid Jamik Bengkulu dapat disintesiskan ke dalam tiga lapisan yang saling terkait dan tak terpisahkan:
Warisan Sejarah: Ia adalah saksi bisu dari dinamika sosial, ekonomi, dan politik Kota Bengkulu. Lebih dari itu, ia adalah penanda fisik dari salah satu periode paling krusial dalam kehidupan Bung Karno, masa pengasingan di mana ia terus mengasah gagasan-gagasan kebangsaannya, bahkan melalui medium arsitektur.
Warisan Arsitektur: Sebagai sebuah karya, masjid ini adalah contoh paripurna dari "Gaya Indonesia" yang diusung Soekarno. Ia secara cemerlang memadukan fungsi sebagai tempat ibadah, filosofi luhur ajaran Islam, dan ideologi nasionalisme dalam satu kesatuan wujud yang harmonis. Setiap elemennya, dari atap tumpang hingga kemuncak Gada Bima, adalah sebuah "teks" yang menyuarakan identitas budaya Nusantara yang plural dan berdaulat.
Warisan Sosial: Hingga hari ini, Masjid Jamik tetap menjadi pusat komunitas yang hidup dan relevan. Ia bukan sekadar artefak yang dikagumi dari kejauhan, melainkan ruang publik yang aktif melayani kebutuhan spiritual, pendidikan, dan sosial masyarakat Bengkulu, serta berfungsi sebagai jembatan pemersatu.
Menatap ke depan, tantangan terbesar yang dihadapi Masjid Jamik Bengkulu adalah menavigasi "paradoks pelestarian"—menyeimbangkan mandat konservasi sebagai cagar budaya dengan kebutuhan fungsional sebagai pusat komunitas yang dinamis. Rencana pemugaran yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu pada tahun 2025 akan menjadi ujian krusial. Keberhasilannya akan sangat bergantung pada kemampuan untuk melakukan restorasi yang cermat dan otentik, sambil mungkin secara kreatif mengintegrasikan solusi-solusi modern yang tidak merusak esensi historisnya.
Pelestarian Masjid Jamik Bengkulu, pada akhirnya, adalah sebuah tanggung jawab kolektif. Ia memerlukan sinergi antara pemerintah sebagai fasilitator dan regulator, para ahli cagar budaya sebagai pemandu teknis, pengurus masjid sebagai operator harian, dan masyarakat luas sebagai pemilik dan penjaga warisan. Memastikan bahwa mahakarya arsitektur Soekarno ini tidak hanya bertahan sebagai bangunan yang terawat, tetapi juga terus berkembang sebagai ruang publik yang bermakna, adalah cara terbaik untuk menjaga nyala api sejarah dan spiritualitasnya tetap hidup bagi generasi-generasi yang akan datang.
















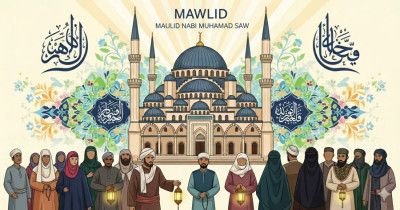

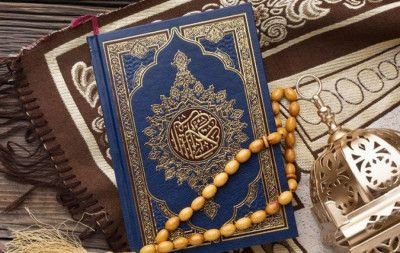

 Pertanian
Pertanian Budaya
Budaya Kesehatan
Kesehatan Fashion
Fashion Diaspora
Diaspora Anak Muda
Anak Muda Konser
Konser Transportasi
Transportasi Ekonomi
Ekonomi
0 Comments