BENGKULU, Caribengkulu.com– Di jantung Kota Bengkulu, berdiri sebuah markah tanah yang melampaui fungsinya sebagai artefak historis: Monumen Tugu Thomas Parr. Tugu ini adalah perwujudan dari narasi ganda yang saling bertentangan. Di satu sisi, ia adalah tugu peringatan yang didirikan oleh pemerintah kolonial Inggris untuk mengenang seorang Residen yang terbunuh; di sisi lain, ia telah direinterpretasi oleh masyarakat Indonesia sebagai simbol perlawanan sengit terhadap penindasan kolonial. Berita ini akan menelusuri konteks sejarah kehadiran East India Company (EIC) di Bengkulu, kebijakan-kebijakan kontroversial Residen Thomas Parr yang memicu pembunuhannya pada tahun 1807, dan pembangunan monumen sebagai pernyataan kekuasaan yang disengaja melalui arsitektur Neoklasik. Lebih lanjut, berita ini akan mendalami bagaimana masyarakat lokal secara aktif merebut dan mengubah makna monumen tersebut, serta mengkaji tantangan-tantangan kontemporer terkait pelestarian dan perannya dalam lanskap perkotaan modern Bengkulu.
Wadah Pendidihan Kolonial Bencoolen: Inggris Menancapkan Kuku di Pesisir Sumatra
Kehadiran East India Company (EIC) di Bengkulu pada tahun 1685 merupakan sebuah langkah strategis yang lahir dari persaingan ketat dengan Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC). Setelah VOC berhasil memonopoli perdagangan lada di Banten, EIC terpaksa mencari pangkalan baru untuk mengamankan kepentingannya dalam perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan. Bengkulu, yang saat itu dikenal sebagai Bencoolen, dipilih karena lokasinya yang strategis di pesisir barat Sumatra, menjadikannya pusat potensial untuk perdagangan lada dan jalur logistik utama di kawasan tersebut.
Kehadiran awal Inggris ditandai dengan pembangunan Benteng York pada tahun 1685 oleh Ralph Ord. Benteng ini berfungsi sebagai pangkalan dagang, barak militer, dan benteng pertahanan pertama Inggris di Sumatra. Namun, Benteng York dibangun di lokasi yang tidak strategis dan terbukti rapuh, serta menjadi sarang wabah penyakit yang menewaskan banyak pasukan Inggris. Kegagalan ini mendorong Gubernur Joseph Collett untuk membangun benteng baru yang jauh lebih kuat dan permanen antara tahun 1714 dan 1719.
Benteng baru ini diberi nama Benteng Marlborough dan dirancang sebagai benteng pertahanan terkuat kedua milik Inggris di wilayah timur, setelah Benteng St. George di Madras, India. Transisi dari Benteng York yang bersifat sementara ke Benteng Marlborough yang monumental bukan sekadar peningkatan logistik; ia melambangkan pergeseran fundamental dalam strategi kolonial Inggris. Ini menunjukkan komitmen jangka panjang untuk tidak hanya berdagang, tetapi juga mengakar dan mengonsolidasikan kekuasaan administratif dan militer di wilayah tersebut. Pembangunan benteng yang kokoh ini secara langsung menciptakan landasan bagi penerapan kebijakan yang lebih intervensionis dan agresif di masa depan, seperti yang akan diberlakukan oleh Thomas Parr.
Selama 140 tahun kehadirannya, hubungan antara EIC dan masyarakat serta penguasa lokal Bengkulu diwarnai oleh kompleksitas dan ketegangan. Meskipun pada awalnya terjalin perjanjian dengan para pangeran lokal untuk berdagang dan membangun benteng, hubungan ini secara inheren tidak seimbang dan sering kali berujung pada konflik akibat kepentingan yang saling bertabrakan.
Keresidenan Thomas Parr (1805-1807): Sebuah Benturan Dunia yang Memantik Api Perlawanan
Thomas Parr tiba di Bengkulu dan diangkat sebagai Residen pada 27 September 1805, menjadikannya penguasa Inggris ke-49 di wilayah tersebut. Pengangkatannya menandai perubahan nomenklatur dari "Wakil Gubernur" menjadi "Residen," yang mungkin mengindikasikan pergeseran fokus administratif. Sejak awal, citra Parr terbelah menjadi dua. Dari perspektif Inggris, seperti yang tertulis di prasasti monumennya, ia digambarkan sebagai "Bapak yang baik hati" (a benevolent Father) bagi penduduk Melayu. Sebaliknya, sumber-sumber Indonesia dan narasi lokal melukiskannya sebagai sosok yang "angkuh dan ganas," yang secara konstan mencampuri urusan adat istiadat masyarakat Bengkulu.
Salah satu kebijakan Parr yang paling berdampak adalah pengenalan budidaya kopi secara besar-besaran dengan sistem tanam paksa. Kebijakan ini merupakan disrupsi langsung terhadap tatanan ekonomi lokal yang secara tradisional bergantung pada komoditas seperti lada, pala, dan cengkih. Meskipun istilah Cultuurstelsel lebih identik dengan era Belanda, prinsip pemaksaan untuk menanam komoditas ekspor demi keuntungan kolonial adalah sama. Kebijakan ini bukan lahir dari kekejaman pribadi semata, melainkan implementasi logis dari doktrin ekonomi kolonial EIC yang saat itu menghadapi tekanan finansial dan melihat kopi sebagai komoditas yang sedang naik daun di Eropa.
Kebijakan Parr tidak hanya menyasar bidang ekonomi, tetapi juga tatanan sosial dan hukum masyarakat Bengkulu. Ia secara aktif mencampuri dan berusaha menghapus hukum adat (adat) lokal. Tindakannya mencakup pencopotan gelar para pemimpin dan pemuka adat, yang dianggap sebagai serangan langsung terhadap martabat dan struktur sosial masyarakat. Dari sudut pandang kolonial, hukum adat dan otoritas pemimpin lokal merupakan penghalang bagi efisiensi sistem tanam paksa kopi. Oleh karena itu, serangan terhadap adat menjadi langkah yang diperlukan untuk mematahkan perlawanan dan membuka jalan bagi tatanan ekonomi baru yang diinginkan EIC. Kombinasi dari eksploitasi ekonomi dan penghinaan terhadap institusi sosial inilah yang pada akhirnya menyulut api perlawanan yang fatal.
Pemberontakan 1807: Malam Pembalasan dan Respons Kolonial yang Brutal
Pada malam tanggal 27 September 1807 (beberapa sumber menyebut 23 Desember 1807), puncak kemarahan rakyat Bengkulu meledak. Sekelompok penyerang berhasil memasuki kediaman Parr, yang dikenal sebagai Mount Felix (atau Bukit Palik oleh penduduk lokal), dan membunuhnya secara brutal dengan menikam dan memenggal kepalanya. Ajudannya, Charles Murray, juga terluka parah dalam serangan itu dan meninggal beberapa waktu kemudian. Serangan ini bukanlah amuk massa yang membabi buta; ia bersifat terarah, karena keluarga Parr dilaporkan tidak dilukai, yang mengindikasikan targetnya adalah simbol otoritas kolonial itu sendiri.
Meskipun beberapa sumber menduga pelakunya adalah anggota keamanan dari etnis Bugis yang perannya dikurangi oleh Parr, konteks yang lebih luas menunjukkan bahwa insiden ini merupakan hasil dari konspirasi yang lebih besar yang lahir dari kemarahan rakyat terhadap kebijakan-kebijakannya yang menindas. Tindakan memenggal kepala Parr merupakan sebuah isyarat simbolis yang kuat, menandakan penolakan total dan penghinaan tertinggi terhadap kekuasaannya. Peristiwa ini harus dipandang bukan sebagai tindakan kriminal biasa, melainkan sebagai sebuah aksi politik—bentuk keadilan rakyat ketika semua saluran diplomatik dan protes damai telah ditutup oleh pemerintahan kolonial yang represif.
Reaksi EIC terhadap pembunuhan residennya sangat cepat dan kejam. Mereka memadamkan pemberontakan dengan kekuatan militer penuh, termasuk menghancurkan dusun-dusun di sekitarnya seperti Sukarami dan Pagar Dewa sebagai tindakan balasan. Respons brutal ini menggarisbawahi ketidakseimbangan kekuatan dan tekad kolonial untuk mempertahankan kendali melalui teror, sekaligus menunjukkan betapa terpukulnya martabat mereka akibat peristiwa tersebut.
Monumen yang Ditempa dalam Konflik: Arsitektur Kekuasaan dan Propaganda Kolonial
Setahun setelah pembunuhan, pada tahun 1808, pemerintah Inggris mendirikan sebuah monumen untuk Thomas Parr. Pembangunan ini lebih dari sekadar untuk menghormati seorang kolega yang gugur. Ia adalah sebuah tindakan perang psikologis yang diperhitungkan. Monumen ini dibangun dengan kerja paksa rakyat lokal, mengubah penduduk yang memberontak menjadi partisipan yang tidak rela dalam glorifikasi penindas mereka. Lokasinya yang strategis, sangat dekat dengan Benteng Marlborough dan gedung dewan pemerintahan EIC, dipilih secara sengaja sebagai pengingat permanen akan kekuasaan Inggris dan konsekuensi fatal dari menentang mereka.
Jenazah Thomas Parr sendiri tidak dimakamkan di lokasi monumen. Karena pertimbangan keamanan dan untuk menghindari penodaan, jenazahnya dimakamkan di dalam kompleks Benteng Marlborough yang dijaga ketat. Keputusan praktis ini juga membawa bobot simbolis yang signifikan: sebuah pengakuan diam-diam bahwa di luar tembok benteng, otoritas Inggris tidaklah mutlak dan selalu berada di bawah ancaman. Dengan demikian, monumen itu sendiri berdiri sebagai artefak utama dari operasi kontra-pemberontakan kolonial—sebuah senjata dalam perang narasi yang bertujuan untuk mengukuhkan versi sejarah sang pemenang.
Monumen Thomas Parr memiliki denah berbentuk segi delapan (oktagonal) yang mencakup area seluas 70 meter persegi. Tingginya mencapai 13,5 meter dan dimahkotai oleh sebuah kubah. Bentuk atap yang membulat inilah yang membuatnya dikenal oleh masyarakat setempat dengan sebutan Kuburan Bulek (Kuburan Bulat). Bangunan ini memiliki tiga pintu masuk berbentuk lengkung dan dikelilingi oleh enam pilar penyangga.
Gaya arsitektur monumen ini adalah Neoklasik, yang terinspirasi dari arsitektur Yunani dan Romawi kuno. Pilar-pilarnya diidentifikasi sebagai gaya Tuscan atau Doric Romawi, meskipun ada juga yang menyebutnya gaya Corinthian. Pilihan gaya ini bukanlah kebetulan. Pada abad ke-18 dan ke-19, Neoklasik adalah bahasa arsitektur kekaisaran, digunakan oleh kekuatan kolonial seperti Inggris untuk memproyeksikan citra keteraturan, rasionalitas, dan keagungan imperial. Dengan menanamkan sebuah karya arsitektur Eropa di jantung kota Bengkulu, EIC secara simbolis menegaskan superioritas dan keabadian peradaban Barat atas budaya lokal yang ingin mereka kuasai. Ini adalah bentuk penyingkiran budaya yang disengaja, sebuah kolonisasi arsitektural yang pesannya sekuat prasasti yang tertulis di dalamnya.
Awalnya, monumen ini berdiri di dekat pusat pemerintahan EIC. Seiring berjalannya waktu, kawasan di sekitarnya telah bertransformasi menjadi area komersial yang ramai, dengan deretan toko dan sebuah kantor pos peninggalan Inggris yang terletak di dekatnya. Perubahan fungsi lingkungan ini secara signifikan memengaruhi persepsi dan pemanfaatan monumen di era modern.
Di dalam monumen ini pernah terdapat sebuah plakat kayu yang kini tulisannya sudah tidak terbaca lagi. Namun, Alan Harfield dalam bukunya pada tahun 1985 berhasil mencatat sebagian isinya. Prasasti tersebut menggambarkan narasi sepihak dari sudut pandang Inggris. Analisis kritis terhadap bahasa prasasti mengungkapkan strategi retorika kolonial yang khas. Frasa-frasa yang digunakan secara sengaja membangun citra tertentu sambil mengaburkan kenyataan yang terjadi. Misalnya, deskripsi Parr sebagai "Bapak yang baik hati bagi penduduk Melayu" dan "bersemangat untuk meningkatkan Kebebasan dan Kesejahteraan mereka" adalah retorika paternalistik klasik yang menutupi sifat eksploitatif pemerintahannya. Kebijakannya, seperti tanam paksa kopi dan penghapusan adat, justru menimbulkan penderitaan dan kemarahan luas. Frasa seperti "gugur tanpa... dan kekejaman yang tak tertandingi di bawah [tangan] yang tersesat" adalah tropus kolonial untuk mendehumanisasi perlawanan pribumi, mengabaikan penyebab utama pemberontakan dan membingkai perlawanan sebagai tindakan irasional. Selain plakat kayu tersebut, dilaporkan pernah ada beberapa tulisan lain dari batu nisan, termasuk untuk Parr dan Charles Murray, yang kemudian dipindahkan ke dalam Benteng Marlborough demi keamanan. Langkah ini semakin memperkuat gagasan bahwa monumen ini adalah sebuah pos terdepan simbolis di wilayah yang dianggap musuh, dan bahwa narasi kolonial yang ingin ditampilkannya sangat rentan terhadap penolakan.
Reinterpretasi Warisan Kolonial: Dari Monumen Parr menjadi Tugu Peringatan Rakyat
Inilah inti dari kisah monumen ini: pergeseran makna yang radikal. Bagi Inggris, monumen ini adalah penanda tragedi dan pengingat akan pengorbanan seorang pejabatnya. Namun, bagi masyarakat Bengkulu, bangunan yang sama memiliki arti yang sama sekali berbeda.
Masyarakat Bengkulu telah secara aktif merebut kembali narasi monumen ini. Ia tidak lagi dilihat sebagai tugu untuk Parr, melainkan sebagai tugu peringatan atas keberanian nenek moyang mereka dalam melawan penindasan, mempertahankan hak atas tanah, dan menjaga adat istiadat. Monumen ini diinterpretasikan ulang sebagai penghargaan untuk para "pahlawan yang tak dikenal" yang gugur dalam perjuangan melawan kolonialisme Inggris. Proses ini adalah contoh kuat dari "perlawanan memori" (memory resistance), di mana sebuah komunitas pascakolonial secara sadar mengambil alih narasi sebuah ruang fisik, membalikkan tujuan aslinya untuk menciptakan identitas baru yang memberdayakan.
Evolusi nama monumen ini mencerminkan pergeseran makna tersebut. Inggris menyebutnya "Parr Monument." Kalangan elite pribumi di kemudian hari sempat menyebutnya "Taman Raffles" (Raffles Park). Namun, nama yang paling melekat dan digunakan oleh masyarakat luas adalah nama deskriptif yang netral, "Kuburan Bulek". Keragaman nama ini merangkum lapisan-lapisan memori yang melekat pada situs tersebut, dari narasi kolonial, elite lokal, hingga persepsi rakyat jelata.
Saat ini, Monumen Thomas Parr telah bertransformasi menjadi ruang publik yang dinamis dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari di jantung Kota Bengkulu. Setiap hari, area di sekitar monumen ini ramai dengan berbagai kegiatan. Para pedagang kaki lima menjajakan dagangannya, warga berolahraga seperti joging di pagi dan sore hari, dan keluarga-keluarga berkumpul untuk bersantai menikmati suasana kota. Tempat ini juga menjadi lokasi berkumpulnya anak-anak muda, terkadang untuk bermain papan seluncur (skateboard). Paradoks yang menarik muncul dari transformasi ini: sebuah situs yang lahir dari kekerasan ekstrem dan penindasan kolonial kini berfungsi sebagai ruang komunal yang damai dan biasa. Proses "domestikasi" ini, di mana monumen diintegrasikan ke dalam ritme kehidupan sehari-hari, secara efektif menetralkan trauma historisnya dan menjauhkannya dari niat kolonial aslinya. Dengan menjadi latar belakang kehidupan alih-alih sebuah pelajaran sejarah yang didaktik, masyarakat Bengkulu telah sepenuhnya mengklaim ruang ini sebagai milik mereka, sebuah proses reklamasi yang terjadi secara organik melalui denyut nadi kehidupan kota.
Pelestarian, Tantangan, dan Masa Depan Situs Warisan: Menjaga Memori yang Berdenyut
Sebagai pengakuan atas nilai historisnya, Monumen Tugu Thomas Parr secara resmi ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya Indonesia pada tahun 2004. Status ini memberikan perlindungan hukum terhadap bangunan tersebut. Pengelolaan monumen ini berada di bawah yurisdiksi Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah VII Bengkulu dan Lampung, yang sebelumnya dikenal sebagai Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jambi. BPK sebagai lembaga pemerintah pusat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu dalam upaya pelestariannya. Untuk perawatan sehari-hari, ditugaskan juru pelihara (kuncen) di lokasi tersebut.
Namun, manajemen cagar budaya tidak luput dari tantangan. Sebuah insiden pada tahun 2017 menjadi contoh nyata. Saat itu, dinas pemerintah kota mengecat kubah monumen dengan warna biru, menyimpang dari warna aslinya yaitu putih. Tindakan ini memicu protes keras dari komunitas peduli warisan budaya, seperti Bengkulu Heritage Society (BHS), dan teguran resmi dari BPCB Jambi yang menuntut agar warnanya dikembalikan seperti semula. Kasus ini menyoroti adanya ketegangan antara inisiatif pemerintah daerah, prinsip-prinsip konservasi yang otentik, dan peran penting advokasi masyarakat dalam menjaga kelestarian cagar budaya.
Beberapa laporan mencatat bahwa pengetahuan pengunjung, dan bahkan sebagian pemandu wisata, tentang sejarah mendalam monumen ini masih terbatas. Fokus sering kali lebih tertuju pada Benteng Marlborough atau Rumah Pengasingan Bung Karno. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk materi edukasi yang lebih baik dan pelatihan bagi pemandu wisata agar dapat merangkai situs-situs sejarah di Bengkulu menjadi sebuah narasi yang utuh dan saling terhubung.
Meskipun berstatus cagar budaya, monumen ini menghadapi tantangan perawatan. Bagian dalamnya pernah ditutup dengan pintu jeruji untuk mencegah vandalisme dan kerusakan akibat digunakan sebagai tempat berkumpul. Lokasinya yang berdekatan dengan Pasar Barukoto dan fungsinya sebagai ruang publik yang intensif menciptakan tantangan kebersihan dan pemeliharaan yang berkelanjutan. Telah ada usulan akademis untuk merevitalisasi seluruh kawasan, termasuk monumen dan pasar di sebelahnya, untuk mengintegrasikan fungsi historis dan komersialnya secara lebih baik.
Kesimpulan: Warisan Ganda dalam Batu dan Memori yang Terus Berdenyut
Monumen Tugu Thomas Parr lebih dari sekadar bangunan peninggalan kolonial; ia adalah sebuah medan pertempuran memori. Secara fisik, ia mewujudkan narasi kekuasaan kolonial, sementara maknanya secara aktif dibentuk dan ditumbangkan oleh kontra-narasi pascakolonial. Nilai terbesar monumen ini justru terletak pada ketegangan yang melekat padanya. Ia menjadi alat edukasi yang luar biasa kuat karena tidak hanya menceritakan satu sejarah, tetapi dua sejarah secara bersamaan: kisah arogansi kolonial dan kisah perlawanan rakyat.
Masa depan pengelolaan warisan budaya dan promosi pariwisata untuk situs ini tidak seharusnya menghindar dari kompleksitas tersebut. Sebaliknya, materi interpretatif harus secara eksplisit menyajikan kedua narasi—perspektif kolonial Inggris dan kisah perlawanan Indonesia. Dengan demikian, Monumen Thomas Parr dapat berfungsi secara optimal sebagai situs untuk refleksi kritis tentang sifat sejarah yang multifaset, sering kali menyakitkan, dan selalu terbuka untuk ditafsirkan kembali.














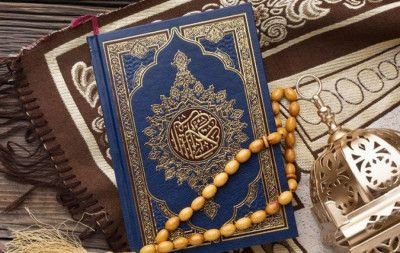




 Keamanan
Keamanan Kesenian
Kesenian Diaspora
Diaspora Sejarah
Sejarah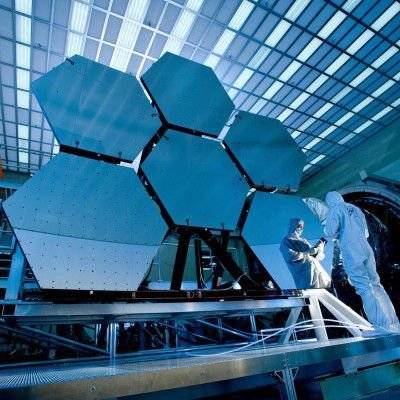 Teknologi
Teknologi Energi
Energi Anak Muda
Anak Muda Kelautan
Kelautan Ekonomi
Ekonomi
0 Comments